(a) Why is the investigation, in Java especially, so backward?
(b) What are the best means to remedy this lack of stabibility in the somatological investigation of Nousantara?
(c) Why have so few Dutchmen participated in the investigation of the Netherlandss East Indies?
Pertanyaan-pertanyaan ini diungkap oleh J. H. Nyéssen dalam bukunya berjudul Somatical Investigation of the Javanese (Bandoeng: Vorkink Comp, 1929) dalam rangka melihat perkembangan penelitian deskripsi dan distinksi bentuk-bentuk manusia di Nusantara. Nyéssen mensinyalir beberapa hal berkontribusi terhadap keterbelakangan riset di negeri jajahan Belanda saat itu. Pertama, adanya usaha-usaha untuk mengabaikan nilai-nilai ideal orang Belanda bersamaan dengan munculnya persaingan tidak sehat sesama peneliti sehingga yang mengakibatkan perpecahan dari dalam. Dia menganggap bahwa orang-orang Belanda di tanah tropis juga sudah terpesona oleh kemewahan yang berakibat berkurangnya kekuatan-kekuatan yang kreatif (Nyéssen, 5). Kedua, penelitian-penelitian somatis masih sangat terbatas pada kalangan Cina dari bagian selatan (terutama dari Hankow dan Shantung), Arab dari Hadramauth, India keturunan Inggris, orang dari Afghanistan dan yang berasal dari Iran (Nyéssen, 5). Penelitian genetis yang dilakukan terhadap pribumi masih dianggap kurang. Yang sudah dilakukan hanya di daerah Toegoe dan terhadap para narapidana (7). Ketiga, adanya pendapat tentang tidak perlunya institusi riset di luar pemerintahan. Padahal menurut Nyéssen, “offisialisme itu bertentangan dengan semangat sain yang menginginkan kebebasan” (8). Investigasi yang terkurung dalam ruang lingkup offisialisme melahirkan peneliti yang amatir “‘amateur’-investigator” karena kesibukan administrasi. Peneliti administratif (Scientist-Official) tidak bisa banyak diharapkan untuk lebih produktif dan kreatif. Walaupun Nyéssen mengkritik penelitian oleh para tenaga administratif, dalam kesimpulan buku ini, dia menyatakan bahwa pemerintah kolonial telah memfasilitasi identifikasi ras Jawa dari Barat sampai ke Timur. Secara umum ras Jawa memiliki kesamaan dengan leluhur mereka yang berasal dari Timur, seperti Mongolia dan dari Barat seperti Australia Dravidian (106).
Nyéssen menyampaikan pendapat beliau tentang perkembangan antropologi di daerah jajahan dalam rangka membuat argumen untuk penelitian somatis masyarakat Jawa sebagai basis dalam memahami perbedaan bentuk-bentuk fisik penduduk nusantara dan meningkatkan kompetensi sain. Dalam pikirannya, sain merupakan aset sebuah masyarakat; untuk itu perlu menjadi bagian dari kehidupan dari universitas di negara tersebut (24). Walaupun Nyéssen berargumen tentang perlunya sain dalam kontek nusantara, dia menilai pendidikan di terapkan bersifat agak aneh. Keanehan ini terletak pada cara pendidikan yang diperkenalkan ke dalam dalam lingkungan Timur ini adalah tiruan dari sistem dan metoda Barat (24). Dia melihat bagaimana ilmu-ilmu yang lahir di Barat seperti Geologi, botani, zoologi dan bahkan kedokteran diterapkan di Nusantara. Sama halnya, ilmu antroplogi juga masih menggunakan teori-teori asing di Barat atau di luar Nusantara dan diterapkan di sini. Pendekatan-pendekatan seperti ini menghambat perkembangan keilmuan yang berdasarkan kebutuhan, kontek, dan topografi Nusantara (25).
Nyéssen termasuk berani untuk memperlihatkan bahwa sain di zaman penjajahan hanya untuk menandakan adanya ekpedisi sebagai upaya untuk memahami daerah-daerah yang perlu untuk ditaklukkan dan membangun romatisme ‘indahnya’ expedisi dalam imaginasi publik (26). Kritik ini disertai dengan perlunya pengembangan sain dalam kontek Nusantara dan didokumentasikan dalam data-data yang tersimpan di tanah air. Harapan Nyéssen ini sudah tentu diarahkan kepada para peneliti yang menjadi bagian atau membantu pemerintah penjajah. Kenyataannya, pendidikan awal mulanya hanya diperuntukan untuk para elit dan bangsawan saja. Ketika pendidikan mulai terbuka untuk umum pada tahun 1980s, tipe pendidikan menjadi dua: untuk elit dan untuk umum (Ricklefs 150-154). Pendidikan tingkat dasar (Meer uitgebreid lager onderwijs [MULO]) biasanya untuk for elite pribumi, China, dan bangsa Eropa lainnya. Sama halnya, sekolah menengah yang didirikan tahun 1919 (Almagemeene Middelbare scholen [AMS]) didirikan dalam rangka menyiapkan calon tenaga administrasi yang membantu penjajah. Anak bangsa yang melanjutkan ke sekolah menengat atas sangat sedikit jumlahnya (the Hoogere burgerschool [HBS]). Sekolah lanjutan selevel university baru buka tahun 1920 yang sekarang menjadi Istitut Teknologi Bandung atau dulunya Technische Hoogeschool. Sekolah hukum (Rechtshoogeschool) berdiri di Jakarta tahun 1924, Selanjutnya, STOVIA atau sekolah kedokteran berdiri tahun 1927. Jadi ketika Nyéssen membuat laporan penelitian tentang ras di jawa pada tahun 1929 belum banyak pribumi yang bisa melakukan penelitian berdasarkan kebutuhan lokasi dan sesuai dengan manusia keindonesiaan.
Siapkah kita pada tahun 2029 melahirkan sain-sain yang ke-Indonesiaan? Ayo berlomba-lomba untuk merumuskan ilmu pengetahuan yang mencerminkan tanah air, manusia, dan budaya kita. Kita perlu bersama menganalisa tentang budaya ofisialisme di tanah air kita. Beranikah kita untuk menyatakan bahwa ofisialisme ini penghambat kemajuan sain di Indonesia? Kita juga diingatkan Nyéssen tentang fenomena peneliti yang amatir “‘amateur’-investigator” karena segala sesuatunya harus dilakukan oleh para pejabat tertentu atau pelaporan penelitian diborong oleh kelompok/penulis tertentu. Praktik seperti ini memunculkan hegemoni relasi kekuasaan antara senior dan junior. Relasi ini tumbuh subur dalam budaya yang disebut Nyéssen sebagai peneliti administratif (Scientist-Official) dimana mereka disibukkan mengurusi laporan perjalan penelitian rekan-rekan peniliti atau ketelitian administrasi. Sudah barang tentu semua ini tantangan bagi kita semua para peniliti dan masih memerlukan penelitian bagaimana roadmap sain kita supaya jaya di negeri sendiri dan dihormati secara global. Merdeka…
Referensi:
J. H. Nyéssen, Somatical Investigation of the Javanese (Bandoeng: Vorkink Comp, 1929).
M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia (London: McMillan, 1981).

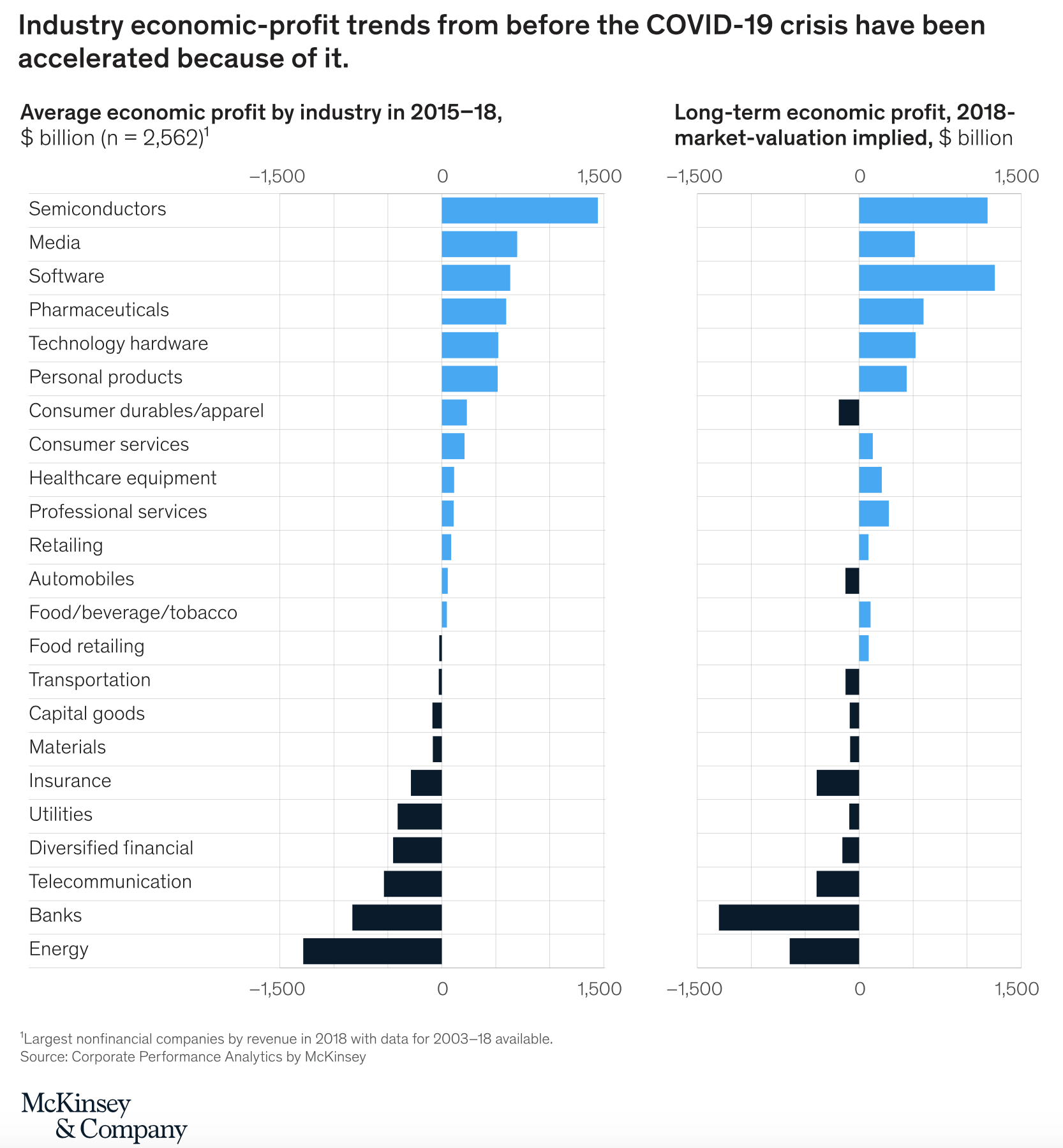


Comments